Puteri tak bisa menutup kekecewaannya. Ibu muda ini baru saja mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar (SD). Sayang, anaknya ditolak di mana-mana karena belum bisa membaca dan menghitung dasar saat mendaftar SD. Puteri akhirnya memutuskan menyekolahkan sang anak di Sekolah Alam kawasan Bintaro.
Dalam angan-angan Puteri, ia ingin mendidik anak-anaknya jauh dari seabrek kegiatan les sana-sini untuk kepentingan mengejar prestasi. Ia tak mau pengalamannya pengalamannya masa kecil terulang pada anaknya. Puteri ingin anaknya menikmati setiap pendidikan yang didapatnya, tanpa perlu dikejar-kejar target akademik yang membuat anak tertekan.
“Dulu jika tidak dapat peringkat satu, pasti langsung dimarahi. Tidak diperbolehkan nonton televisi dan hanya keluar rumah untuk les,” katanya.
Dia menceritakan betapa masa kecilnya kurang membahagiakan. Ia nyaris tak punya waktu untuk bermain. Waktu Puteri habis untuk beragam les mulai dari Bahasa Inggris, Matematika, bela diri, juga les musik. Ibunya sempat berkata, semua itu dilakukan agar perkembangan otaknya seimbang, asah kiri dan asah kanan. Sayang, maksud baik tak selalu berujung apik, Puteri malah memiliki masalah sulit bersosialisasi hingga dewasa. Karena itu, Puteri bertekad anaknya tak boleh senasib dengan dirinya.
Puteri tidak sendiri. Banyak anak Indonesia yang senasib dengannya. Sistem pendidikan dan pola pikir orang tua yang salam membuat anak Indonesia menjadi korban. Mereka harus mengejar target akademik yang tinggi dan tentu saja segudang prestasi. Sekolah dari pagi hingga sore tidak cukup. Mereka harus menambah les di malam hari, juga di akhir pekan. Kebahagiaan anak-anak terenggut oleh sesuatu yang masih sangat diagungkan di Indonesia: Prestasi Akademik.
- Bumerang
Banyak orang tua yang mendorong anak untuk berprestasi akademik. “Semua agar masa depanmu lebih baik.” “Persaingan sangat ketat, kalau kamu tidak menjadi yang terbaik, kamu gagal." Demikian alasan para orang tua yang selalu mendidik keras anak-anaknya.
Amankah jenis pemaksaan akademik semacam itu terhadap tumbuh kembangnya mental anak?
Psikolog Adityana Kasandra Putranto mengatakan, beratnya beban pelajaran yang diterima anak dapat menyebabkan stres dan depresi berat. Dalam beberapa kasus, stres yang diderita dapat diakibatkan oleh banyaknya les yang diikuti.
“Pada pasien saya sendiri memang banyak yang terganggu akibat tekanan akademik, beratnya beban pelajaran membuat mereka tertekan,” jelasnya kepada tirto.id, Rabu (3/7).
Kebanyakan orang tua beranggapan banyak les akan meningkatkan IQ anak. Apalagi, banyak bimbingan belajar yang mengeluarkan jurus “pintar instan” sehingga membuat orang tua tergiur.
Sayang, hal tersebut bisa menjadi bumerang. Dalam beberapa kasus, anak yang dijejali beragam les memang bisa menjadi pintar. Namun, ada yang berkebalikan. Kehilangan waktu bermain, tidak bahagia, tertekan karena banyaknya les bisa membuat prestasi anak malah merosot.
“Biasanya orang tua ambil cara-cara instan yang tidak rasional. Bayar mahal-mahal tapi saat itu tidak berhasil, mereka kembali menumpahkan amarahnya pada anak, dan memberi tekanan yang semakin berat,” ujarnya.
Tingkat depresi anak-anak sendiri cukup beragam. Menurut Hankin & Abramson (1998), puncak depresi akademis banyak terjadi antara usia 15 tahun dan 18 tahun. Tingkat depresi remaja lebih tinggi dikarenakan periode ini banyak tuntutan yang ditujukan kepada remaja, salah satunya pencapaian prestasi akademik yang lebih baik.
Penelitian Shahmohammadi (2011) juga menyimpulkan penyebab stres di kalangan siswa dikarenakan ketakutan tidak lolos di perguruan tinggi, ujian sekolah, terlalu banyak konten pelajaran, dan jadwal sekolah yang terlalu padat.
- Biarkan Anak Belajar Sesuai Usianya
Dalam Teori Piaget, sebenarnya periode perkembangan kognitif anak dibagi menjadi empat: Pertama, Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) yang berkenaan dengan refleks bawaan. Kedua, Periode pra-operasional (usia 2–7 tahun), di mana anak sudah mampu mengklasifikasikan ciri psikologis, seperti mengumpulkan benda berwarna merah menjadi satu kesatuan. Ketiga, Periode operasional konkret (usia 7–11 tahun), anak-anak mulai dapat membedakan logika memadai seperi berhitung. Terakhir, periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) yang sudah bisa menganalisis sesuatu yang abstrak seperti cinta.
Tapi, saat ini yang terjadi di Indonesia, materi pembelajaran dipercepat lima tahun sebelum waktunya. Misal saja pada anak kelas 1 SD sudah harus bisa merumuskan definisi abstrak seperti kemerdekaan, belajar dengan pola bacaan berbentuk paragraf dan harus sudah bisa baca hitung untuk lolos duduk di grade tersebut.
“Sistem pendidikan Indonesia salah karena mengharuskan anak pintar di segala hal, masuk SD umur enam tahun saja sudah harus pandai membaca dan berhitung, sibuk ikut Kumon lah,” kata Kasandra.
Menilik pembelajaran di luar negeri, Australia dan Finlandia, misalnya, lebih mengedepankan aspek pekerti dan keberanian diri saat umur tujuh tahun, seperti misalnya belajar untuk antre dan presentasi. Hasilnya, tentu tak perlu dipertanyakan lagi.
Indonesia terlalu fokus pada cara pendidikan menekan dan menghapal, sehingga anak pada akhirnya tak dapat menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Kasandra mengaku memiliki pasien yang mentalnya terganggu, sering bengong, dan masuk Rumah Sakit Jiwa.
“Ada yang masuk RSJ, tapi umurnya remaja, yang saya pegang 15-21 tahun, bunuh diri karena stres akademik juga ada,” ujarnya.
- Belajar dari Korea
Indonesia sepertinya harus belajar dari Korea Selatan (Korsel). Dalam sebuah survei didapati bahwa banyak pelajar di Korsel mengalami stres. Survei yang dilakukan lembaga nirlaba Asunaro mengungkapkan, pelajar SMA di Korsel menghabiskan 12 jam waktunya untuk belajar di sekolah. Lebih dari 70 persen siswa yang disurvei “merasa bersalah” jika mereka rehat dari belajar. Mereka belajar dengan keras untuk menghadapi ketatnya kompetisi.
Belajar di sekolah belum cukup. Sebanyak 97 persen siswa yang disurvei mengaku sering begadang untuk belajar. Belum cukup sampai di situ, sebanyak 67,3 persen siswa SMU di Korsel mengaku menghabiskan waktunya di akhir pekan untuk melihat lagi bahan pelajaran.
Survei juga menunjukkan, siswa SMA Korsel rata-rata hanya tidur kurang dari enam jam per malam. Sebanyak 41,3 persen siswa merasa bersalah jika sudah selesai belajar pada pukul 10 malam.
Sementara untuk siswa SD dan SMP di Korsel juga menghabiskan sebagian waktunya setelah sekolah untuk les. Sebanyak 76 persen siswa SMP di Korsel mengambil les privat setelah sekolah. Untuk SD, persentasenya mencapai 86 persen. Bruce Lee, direktur Office of International Affairs Yonsei University punya penjelasannya. Mengapa pelajar Korsel sedemikian keras terhadap dirinya?
“Pendidikan sangat penting dan masalah besar dalam budaya dan sosial di Korea,” ujar Lee, seperti dilansir dari www.universityworldnews.com.
“Dalam kasus mahasiswa, mereka sangat kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus, jadi mereka belajar keras,” tambahnya.
Sementara Matthew Hobden, instruktur bahasa Inggris University of Incheon meyakini, pelajar Korsel sedemikian keras belajar karena sejarah negaranya.
“60 tahun lalu, Korea adalah negara yang tercabik-cabik oleh perang, dan sekarang berkembang pesat. Ini dicapai melalui kerja keras. Kerja keras itu ditunjukkan melalui belajar keras, belajar keras dan kamu bisa mencapai semuanya, itu tipe perilakunya,” jelas Hobden.
Obsesi terhadap pendidikan anak tidak selalu berujung baik. Setidaknya berdasarkan riset yang dirilis di The Educational Review, ada gejala meningkatnya tingkat stres akibat pendidikan di Cina. Peneliti menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi beban, seperti lingkungan, menjadi perempuan, murid tingkat atas dan persepsi lingkungan dapat membuat murid menjadi stres.
Masyarakat Cina memang dikenal memiliki obsesi tinggi terhadap pencapaian akademis. Setidaknya berbagai capaian akademis dunia dikuasai oleh siswa-siswa dari Cina. Namun, hal ini punya dampak yang tidak baik, tingkat stres antara siswa sekolah di Cina merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan siswa dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari laporan yang dirilis di Cina sendiri menyebutkan bahwa tingkat stres yang luar biasa pada siswa bisa membawa masalah kesehatan mental, termasuk perasaan menderita, dan kecemasan yang tinggi.
Masyarakat Cina memang dikenal memiliki obsesi tinggi terhadap pencapaian akademis. Setidaknya berbagai capaian akademis dunia dikuasai oleh siswa-siswa dari Cina. Namun, hal ini punya dampak yang tidak baik, tingkat stres antara siswa sekolah di Cina merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan siswa dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari laporan yang dirilis di Cina sendiri menyebutkan bahwa tingkat stres yang luar biasa pada siswa bisa membawa masalah kesehatan mental, termasuk perasaan menderita, dan kecemasan yang tinggi.
Setiap tahun ada 200.000 remaja usia sekolah yang melakukan bunuh diri, sementara empat juta orang menjelang dewasa berusaha melakukan bunuh diri. Angka ini naik terus beberapa tahun terakhir. Menurut statistik dari WHO pada 2011, negara seperti Lithuania, angka kematian remaja karena bunuh diri sangat tinggi.
Sebuah survei di Korea menyebut 20 persen remaja usia sekolah merasa ingin bunuh diri. Sementara di India sekitar 20 remaja anak sekolah bunuh diri setiap hari karena stress terkait ujian dan pendapatkan tempat di sekolah prestis. Angka ini berasal dari India National Crime Records Bureau. India selatan merupakan ibukota bunuh diri dunia, terutama di Kerala, negara bagian India yang secara penuh terbebas dari buta aksara. Setiap hari ada 32 orang bunuh diri.
Stres karena tuntutan untuk mencapai prestasi tinggi di pendidikan membuat seseorang berbuat nekat. Sepanjang September 2015 ada tiga siswa yang melakukan bunuh diri di Hong Kong. Dua korban merupakan siswa sekolah menengah dan satu mahasiswa perguruan tinggi. Ketiga siswa ini dikabarkan mengalami depresi dan stress berat karena tuntutan pendidikan yang terlalu berat. Dalam rentang waktu 2005-2015 di Hong Kong telah terjadi 110 kali peristiwa bunuh diri terkait depresi karena pendidikan yang dianggap terlalu berat.
Gejala bunuh diri akibat tekanan tuntutan pendidikan tidak hanya terjadi di Hong Kong. Korea Selatan menjadi negara kedua di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan tingkat bunuh diri siswa tertinggi. Kualitas pendidikan di Korea Selatan diakui sebagai salah satu yang terbaik di OECD. Namun, tekanan untuk yang menjadi terbaik ini mempunyai harga yang mahal. Pada 2001 angka kematian akibat bunuh diri di Korea Selatan pada kelompok usia 10-19 tahun berkisar antara 3,19 per 100.000. Namun pada 2011 angka itu naik menjadi 5,58 per 100.000 orang.
Sebuah survei di Korea menyebut 20 persen remaja usia sekolah merasa ingin bunuh diri. Sementara di India sekitar 20 remaja anak sekolah bunuh diri setiap hari karena stress terkait ujian dan pendapatkan tempat di sekolah prestis. Angka ini berasal dari India National Crime Records Bureau. India selatan merupakan ibukota bunuh diri dunia, terutama di Kerala, negara bagian India yang secara penuh terbebas dari buta aksara. Setiap hari ada 32 orang bunuh diri.
Stres karena tuntutan untuk mencapai prestasi tinggi di pendidikan membuat seseorang berbuat nekat. Sepanjang September 2015 ada tiga siswa yang melakukan bunuh diri di Hong Kong. Dua korban merupakan siswa sekolah menengah dan satu mahasiswa perguruan tinggi. Ketiga siswa ini dikabarkan mengalami depresi dan stress berat karena tuntutan pendidikan yang terlalu berat. Dalam rentang waktu 2005-2015 di Hong Kong telah terjadi 110 kali peristiwa bunuh diri terkait depresi karena pendidikan yang dianggap terlalu berat.
Gejala bunuh diri akibat tekanan tuntutan pendidikan tidak hanya terjadi di Hong Kong. Korea Selatan menjadi negara kedua di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan tingkat bunuh diri siswa tertinggi. Kualitas pendidikan di Korea Selatan diakui sebagai salah satu yang terbaik di OECD. Namun, tekanan untuk yang menjadi terbaik ini mempunyai harga yang mahal. Pada 2001 angka kematian akibat bunuh diri di Korea Selatan pada kelompok usia 10-19 tahun berkisar antara 3,19 per 100.000. Namun pada 2011 angka itu naik menjadi 5,58 per 100.000 orang.
Jepang tetap menjadi negara dengan angka kematian siswa tertinggi di dunia. Setidaknya menurut data resmi pemerintah Jepang, ada 18.000 bunuh diri anak yang terjadi dari 1972-2013. Hal itu paling banyak terjadi di masa awal masuk sekolah. WHO pada 2014 menyebut, angka kematian akibat bunuh diri di kalangan anak-anak di Jepang 60 persen lebih tinggi daripada angka rata-rata global.
Bunuh diri pada 2014 menjadi penyebab utama kematian anak-anak pada usia 10-19 tahun di Jepang. Sementara itu dalam riset yang dilakukan pada 2005, masalah di sekolah menjadi penyebab utama anak-anak bunuh diri. Hal ini ditemukan dalam catatan bunuh diri siswa tersebut 91 di antaranya menyebutkan sekolah sebagai pusat masalah mereka. 242 kasus lain, meski tidak ditemukan catatan bunuh diri, polisi jepang menyebutkan kematian mereka karena beban pelajaran dan buliying di sekolah.
Indonesia dan Korsel sebenarnya senasib. Keduanya sama-sama pernah dijajah. Indonesia dan Korsel merdeka dalam waktu yang hampir sama. Namun, Indonesia kini bisa dikatakan lebih tertinggal dibandingkan Korsel.
Pertumbuhan pesat dari Korsel mungkin dicapai melalui kerja keras warganya. Sayangnya, kerja keras itu kemudian diterjemahkan dengan mengorbankan kebahagiaan warganya. Untuk hal ini, Indonesia sepertinya harus memetik pelajaran berharga dari Korsel. Tidak ada kemajuan yang akan dicapai jika harus mengorbankan kebahagiaan anak-anak.
*dikutip dari Tirto.id
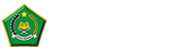






No comments:
Post a Comment